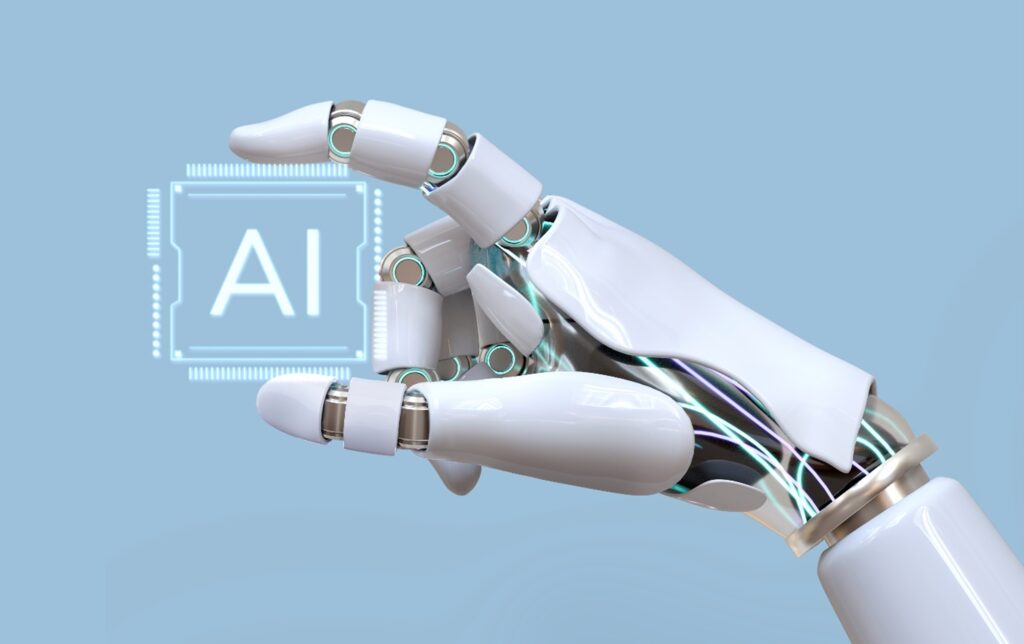Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang diatur di dalam konstitusi Indonesia. Pemenuhan hak atas lingkungan hidup menjadi polemik pada saat ini mengingat kegiatan pembangunan yang destruktif tanpa mempertimbangkan kelestarian alam. World Population Review (WPR) menempatkan Indonesia sebagai negara dengan perusakan hutan terparah pada tahun 2024. Kerusakan hutan memang pada akhirnya akan berdampak terhadap kehidupan seluruh masyarakat Indonesia, namun terdapat kelompok-kelompok yang akan mengalami dampak lebih besar dibandingkan kelompok lainnya.
Masyarakat Hukum Adat merupakan salah satu kelompok rentan yang akan terkena dampak kerusakan hutan sehingga hak atas lingkungan hidup mereka terlanggar. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Katadata tahun 2018, terdapat 70 juta Masyarakat Hukum Adat di Indonesia yang menjadi bagian dari 1.100 suku. Saat ini, Masyarakat Adat Indonesia bertempat tinggal di 10, 86 juta hektar luas wilayah adat di mana 76% wilayah tersebut merupakan kawasan hutan. Masyarakat adat memiliki ikatan erat dengan lingkungan hidup karena mereka menggantungkan kehidupannya dengan kekayaan alam yang disediakan oleh hutan.
Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) disinyalir merupakan terobosan hukum untuk memberikan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Hal ini ditunjukan dengan penempatan kelestarian dan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup sebagai salah satu asas dalam upaya pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan Masyarakat Adat. Asas tersebut menekankan kepada kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya untuk mengelola lingkungan hidup sehingga manusia harus bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan supaya pengelolaannya dapat dilakukan dengan cara cerdas. Ketentuan mengenai hak atas lingkungan hidup di dalam RUU MHA terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) yang menegaskan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak Masyarakat Adat. Bentuk-bentuk konkret tersebut kemudian diatur secara lebih spesifik dalam Pasal 5 ayat (2) RUU MHA sebagaimana berikut:
“Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
c. penerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.”
Bentuk-bentuk pelaksanaan hak di atas tidak hanya berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup, tetapi juga hak atas Free, Prior, dan Informed Consent (FPIC). Penetapan ketentuan ini dapat memberikan prospek baik bagi Masyarakat Adat untuk setuju atau tidak setuju dalam pengambilan keputusan pada proses pembangunan. Selain itu, pengaturan hak ini juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap Masyarakat Adat yang acap kali dikriminalisasi ketika mempertahankan tanah ulayat dan menjalankan kearifan lokal untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Seyogyanya Masyarakat Adat merupakan garda terdepan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan hutan Indonesia. Hal tersebut tersebut semakin mendorong urgensi optimalisasi pemenuhan hak atas lingkungan hidup bagi Masyarakat Adat melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk memasukkan RUU MHA ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 sudah sangat tepat.
Referensi
Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Naskah Akademik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.
Mering, Alexander. Et al. Policy Brief RUU Masyarakat Adat: Menjalin Benang Konstitusi Menuju Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Koalisi Kawal Masyarakat Adat. 2020.
Andriarsi, Melati Krisna. “Sebaran Masyarakat Adat.” Katadata.co, 10 Oktober 2020. Tersedia di https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat. Diakses pada tanggal 17 Februari 2023.
Ningrum, Melinda Kusuma. “WPR: Kerusakan Hutan Indonesia Nomor 2 Terluas di Indonesia.” Tempo.co, 18 Januari 2024. Tersedia di https://www.tempo.co/lingkungan/wpr-kerusakan-hutan-indonesia-nomor-2-terluas-di-dunia–96620. Diakses pada tanggal 5 Desember 2024.
 Artikel hukum ini ditulis oleh Farras Zidane Diego Ali Farhan – Intern DNT Lawyers.
Artikel hukum ini ditulis oleh Farras Zidane Diego Ali Farhan – Intern DNT Lawyers.
Bila Anda ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait persoalan hukum, segera hubungi kami di (021) 2206-4438 atau email: info@dntlawyers.com atau datang ke kantor kami di Dalimunthe & Tampubolon Lawyers (www.dntlawyers.com).